Wartawan Berotak Kiri [1]
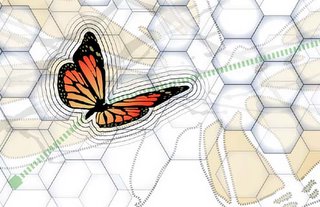 ILLUSTRATED BY MARGARET M. WENDELL
ILLUSTRATED BY MARGARET M. WENDELLProlog: Tulisan ini di bawah ini sebetulnya merupakan makalah, kompilasi dari banyak sumber pustaka. Beberapa kali dipresentasikan di depan para redaktur suatu media dan asosiasi wartawan yang mengundang saya. Beberapa teman lama yang sempat membaca, menilai makalah ini kaya gagasan, informatif. Membaca Wartawan Berotak Kiri, ini kata salah seorang dari mereka, seperti membaca esai bahasa.
-ABT
-------------------------------------------
PERDANA Menteri Inggris pada Perang Dunia I, David Lloyd George, pernah berkata kepada C.P Scott, redaktur harian Manchester Guardian, “Bila semua orang mengetahui hal yang sebenarnya sekarang, perang akan berhenti esok hari. Tapi, mereka tidak tahu dan tidak pernah tahu.”
Tiga belas tahun silam, tentara Amerika Serikat (AS) menyerang Irak. Pertempuran menewaskan penduduk Kurdi dan kaum minoritas Shiah, dua kelompok warga Irak yang dijanjikan perlindungan dari George Bush dan John Major. Media AS memberitakan, serangan itu “hanya memakan sedikit korban”. Jumlahnya, 250 ribu orang.
Pada medio 1998, NATO mengebomi wilayah permukiman di Kosovo, meneror, dan membunuh orang-orang yang dilindungi oleh Clinton dan Blair. “Serangan meleset,” tulis pers di Brussel. Tentara AS menggunakan pesawat tempur A-10 Warthog, lengkap dengan misil uranium. Inilah yang menyebabkan leukemia pada anak-anak di Irak bagian selatan, sesuatu yang mengingatkan kita pada tragedi di Hiroshima. Dalam pemberitaan BBC, dentuman bom di Kosovo disebut “suara malaikat”.
Tak seorang pun meragukan kebrutalan Milosevic, meski PBB telah meredakan ketegangan antara Serbia dan militer Kosovo pada 25 Maret 1998. Simak bagaimana pers Inggris memberi headline: “Milosevic Lebih Kuat dari Sebelumnya, Terima Kasih NATO.”
Bayangkan juga bagaimana Peter Sissons membuka siarannya di radio BBC: “Selamat malam. NATO melanjutkan serangannya dengan membunuh orang-orang sipil tak bersalah di Serbia. Setelah sepekan membantu 10 dari seribu pengungsi yang melarikan diri saat pengeboman, pemerintah Inggris menyumbangkan 20 juta poundsterling. Jumlah itu sama dengan harga dua buah misil.”
* * *
DARI penggalan cerita diatas, saya hanya ingin menarik garis pemisah antara “menemukan peristiwa” dan “menyampaikan peristiwa”. Vitalitas menuntun keberhasilan wartawan “menemukan peristiwa”, tapi, keberhasilan wartawan “menyampaikan peristiwa” dituntun oleh relativitas. Apa yang wartawan temukan di suatu peristiwa, belum tentu sama dengan apa yang ada di medianya. It is not as it was. Berlindung di balik kebajikan media, tindakan “menyampaikan peristiwa” hari-hari ini merupakan kegiatan yang relatif.
Sama dengan adagium gun doesn’t kill, people do, bahasa jurnalistik untuk “menyampaikan peristiwa” hanyalah alat. Lakunya menuruti derajat ketrampilan wartawan. Mereka yang melatih otak kirinya dengan baik dan benar, bisa menjadikan bahasa jurnalistik sebagai alat merekayasa, memanipulasi, atau memolesi fakta. Separo fakta, setengah dusta.
Namun, wartawan juga bisa menjadikan bahasa jurnalistik sebagai alat efektif memantau kekuasaan dan menyuarakan kepentingan warga masyarakat yang tersisih. Di atas kertas, itu soal pilihan. Umumnya, wartawan yang “tahu terlalu banyak” cenderung memilih bahasa jurnalistik yang mengaburkan fakta. Tujuannya, meminimalkan “kesalahan yang tampak” atas kekuasaan dalam perang, terorisme, pelanggaran HAM, skandal, dan lain sebagainya. Itu sebabnya wartawan perang seperti John Pilger percaya bahwa, “Journalists are not giving us the real story.”
Sementara itu, wartawan yang “tahu terlalu sedikit” cenderung memilih bahasa jurnalistik yang melebih-lebihkan fakta. Tujuannya, memaksimalkan “kesalahan yang tak tampak” atas kekuasaan. Itu sebabnya pengacara seperti Adnan Buyung Nasution menggerutu, “Ini merupakan trial by the press, melanggar asas praduga tak bersalah, dan tak akurat.”
Tuduhan-tuduhan diatas tidak sepenuhnya benar. Terkadang wartawan dan media harus melindungi publik dari gambaran kengerian, penderitaan sehari-hari, dan peristiwa hidup yang kelam. Di bawah payung adab dan moralitas, rekaman video atau foto otentik tentang peristiwa berdarah harus disimpan di dalam laci. Demikian pula bahasa jurnalistik yang akan digunakan, harus dipilah-pilih sedemikian rupa. Itu sebabnya kritikus media seperti Joe Saltzman bersungut-sungut, “It is a good taste, bad journalism.”
Era pers gugup-gagap di era orde baru memang telah berlalu. Praktik berbahasa seperti kurang gizi untuk tidak menulis kelaparan tinggal lelucon. Dulu, pers menulis penyesuaian harga tatkala harga kebutuhan bahan pokok naik mengikuti BBM. Pokoknya, apa saja yang dikataken daripada Presiden Soeharto dan petunjuk Menpen Harmoko, media menurunkan beritanya.
Reformasi melimpahkan politik kekuasaan kini sepenuhnya kepada pengiklan, pemilik perusahaan media, tim sukses, serta pejabat humas dan segerombolan orang berpengaruh.
Ledakan media massa yang mengencangkan persaingan antarmedia, di satu sisi dapat mengendurkan self control terhadap bingkai-bingkai kepatutan. Pada saat bersamaan, media dapat menjadi sangat toleran terhadap kesalahan tampak sumber berita yang kebetulan seorang teman.
Situasi ini mendorong pengelola media massa mengonsolidasi kekuatannya demi kepentingan pragmatis. Bahasa jurnalistik sebagai salah satu elemen kekuatan media terkonsolidasi pada pragmatisme tersebut. Ujungnya, praktik berbahasa tidak lagi menjadi petualangan intelektual yang mengasyikkan di kalangan wartawan. Sebab, politik kekuasaan yang mendistorsi praktik berbahasa, nyaris tak menyisakan ruang bagi tumbuhnya eksperimen dalam berbahasa. Entah soal struktur, langgam, pilihan lead, dan teknik penulisan satu reportase dengan lainnya dibuat nyaris sama. Tapi, “Who cares? Emang gue pikirin?”
Paralel dengan itu, para penyunting/redaktur kita umumnya menempatkan diri sebagai “penghalus”. Mereka bagaikan kertas ampelas yang digosokkan pada berbagai bentuk keaslian. Garis yang membentang antara jurnalisme yang cakap dan sikap orisinalitas semakin kabur. Mereka masih mengurusi telur atau telor, apotik atau apotek, atlit atau atlet, karir atau karier. Mereka lebih suka mencermati teks, tapi malas memeriksa konteks tulisan.


<< Home