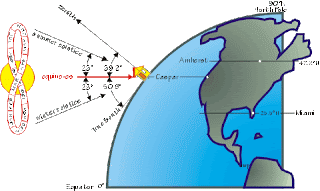Negara, Agama, KTP, dan Salah Kaprah
 ILLUSTRATED BY EGLON VAN DER NEER
ILLUSTRATED BY EGLON VAN DER NEERSenang membaca karya jurnalisme bertitel Negara, Agama dan KTP di Majalah Playboy Indonesia edisi I, April 2006. Meminjam kata-kata almarhum Pak Tino Sidin, “Bagus, bagus, kirim lagi karya-karya yang lain.” Saya baru tahu kalau penghayat ajaran Konghucu, Kejawen, Aliran Mulajadi Nabolon, Purwoduksino, Budi Luhur, Kaharingan, Pahkampetan, Bolim, Basora, Tonaas Walian, dan lain-lain itu punya KTP dengan tanda strip (-) pada kolom agama.
Satu-satunya yang kurang bagus (ini kata saya, bukan Pak Tino), karya itu tidak memiliki cukup kekritisan baik dalam konteks analisis maupun konteks empiris; dua konteks utuh yang menentukan keseriusan karya bertema agama dan politik kekuasaan. Sebaliknya, Agus Sopian, penulisnya, mereduksi pilihan tema tersebut menjadi isu usang: ketidakadilan.
Dari aspek kesejarahan, Kang Agus mengalpakan diskursus serupa di sebagian kelompok intelektual soal pencantuman agama dalam KTP. Jangan lupa, tahun 1990-an di kota-kota terpelajar seperti Jakarta, Yogyakarta dan Semarang, pernah muncul – meski dalam tataran wacana – perlawanan terhadap pencatatan agama seseorang di KTP. Pencantuman golongan darah cukup masuk nalar (make sense), lantaran diperlukan sekiranya saya apes keserempet truk gandeng dan harus dioperasi dengan tambahan darah PMI. Tapi, apa urusannya agama seseorang dicantumkan di KTP? Bukahkah agama, kepercayaan atau tidak bergama pun merupakan urusan privat-spiritual masing-masing individu? Kelompok ini sudah lama mengenali, mencurigai bahwa pencantuman agama dalam KTP sebagai salah satu penyebab politik diskriminasi. Bahkan ada lelucon, jangan-jangan pencantuman agama di KTP Indonesia nanti jadi begini: Islam NU atau Islam Muhammadiyah; Katolik Roma atau Katolik Ortodoks. Protestan metodis atau Protestan fundamentalis. Dan seterusnya.
Kalau Anda tanyakan ini ke Menteri Agama, paling-paling ia bilang, “Karena negara ini bukan negara sekuler.” Tapi kalau Anda tanyakan ke FPI, paling banter mereka bilang, pencantuman agama di KTP diperlukan sekiranya seseorang meninggal, jauh dari tempat tinggal serta kerabat dekat dan mesti lekas dikubur sesuai tradisi agama pemeluknya. Memangnya énté mau dikubur dengan diurug tanah begitu saja?
Konsep “langage” dari pemikir Islam Ulil Abshar-Abdalla untuk merumuskan bentuk dan wujud iman, sebetulnya entry point yang tepat sebelum mengeksplorasi tema – sebagaimana tercermin lewat judul tulisan – agama dan politik kekuasaan. Sayangnya, di sekujur tulisan tak ada penjelasan antropologis yang menguatkan alasan-alasan politis negara atau kerajaan di masa silam “mendikte” agama rakyatnya. Suatu zaman yang disebut-sebut sebagai sistem sosial prademokrasi, menurut saya, tidak akurat letak historisnya karena agama atau kepercayaan di masa-masa itu cukup beragam. Pelbagai kepercayaan yang menyandarkan keilahian alam dan agnostik – yang direduksi maknanya sebagai animisme dan ateis – lebih banyak daripada agama formal Hindu atau Budha waktu itu. Bahkan ketika agama langit seperti Islam diikuti Kristen Barat masuk, pluralisme di masa itu justru menjadi sesuatu yang jamak. Negara dan raja tak berselera mencampuri kepercayaan rakyatnya terlampau jauh. Yang mengagumkan, di tengah keberagaman kepercayaan itu mereka tak berkelahi memperebutkan truth claims sebagaimana pertempuran hidup-mati pada agama monoteis: Yahudi, Kristen, dan Islam.
Alih-alih ingin mengampanyekan pluralisme, Mutjaba Hamdi, seorang aktivis lintas agama dari Jakarta yang juga salah seorang sumber tulisan, malah memicu salah kaprah. Sebab, Injil yang dipahami Hamdi samasekali berbeda dari terminologi umum Kristianitas sendiri. Padahal, Injil hanyalah salah satu bagian kecil dari kitab suci Kristianitas yang disebut Alkitab. Jadi, posisi sentral kitab suci Kristianitas berupa Alkitab hanya dapat disepadankan dengan Al-Qur’an dalam Islam. Alkitab tak lain kumpulan kitab, semacam “perpustakaan portabel” yang memuat kesaksian tentang sabda Allah, ditulis oleh berbagai pengarang dalam kurun 2.000 tahun. Alkitab terbagi atas dua bagian besar: Perjanjian Lama (45 kitab) – yang sudah ada sebelum kelahiran Yesus – dan Perjanjian Baru (27 kitab). Perjanjian Lama terdiri dari lima bagian kecil: lima kitab Pentateukh (5 gulungan kitab atau hukum Musa), 15 kitab sejarah (dengan catatan kitab Ezra dan Nehemia dijadikan satu), tujuh kitab puitis dan hikmat (kebajikan dan mazmur), dan 18 kitab para nabi. Sedangkan Perjanjian Baru berisikan: empat Injil, satu kisah para murid Yesus, 14 surat Paulus, tujuh surat Kristianitas, dan satu kitab Wahyu.
Tak ada risalah teologis yang menyatakan Injil adalah sabda Yesus, seperti pengertian Mutjaba Hamdi yang dikutip Agus Sopian. Asal-usul kata “Injil” yang ditulis oleh Mateus, Markus, Lukas dan Yohanes merupakan turunan bahasa Aramaik – dulu dipergunakan Yesus dan dipentaskan dalam film The Passion of the Christ besutan Mel Gibson (2003) – yang berarti kabar gembira. Bahasa lain menyebutnya Gospel yang berarti ajaran Yesus. Kata Gospel berasal dari Anglo-Saxon, God-Spell, yang artinya “Good Story” (Cerita Baik). Kemudian dari bahasa Latin, Evangelium, yang artinya “Good News,” yaitu Kabar Baik.
Substansi Injil berisikan riwayat kehidupan dan kematian Yesus. Di dalamnya memang tersebar informasi bagaimana perilaku dan ajaran baik Yesus. Meski begitu, saya belum pernah mendengar ada orang Katolik atau Protestan yang menganggap Injil sabda Yesus. Keyakinan bahwa Yesus anak Allah tak berarti Yesus “diizinkan” untuk bersabda. Di Injil sendiri, ditulis dengan “Yesus berkata” atau “kata Yesus.”
Benar jika Injil dapat disepadankan dengan Hadits dalam Islam yang memuat perkataan dan keteladanan Nabi Muhammad, yang diriwayatkan para sahabatnya sebagai rujukan pelengkap Al-Qur’an. Namun, pengertian Injil di sini bukanlah Alkitab atau Kitab Suci Kristianitas yang dikira Hamdi. Dengan demikian, klaim yang menyatakan terdapat bias Islam terhadap posisi sentral kitab suci dan nabi di antara Kristinitas dan Islam tidak benar. Yang ada sekadar salah kaprahnya sendiri soal Injil dan Alkitab.
Cimanggis, 2 Mei 2006