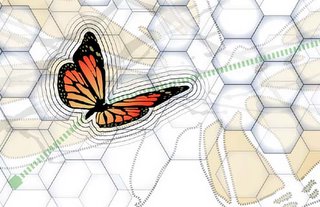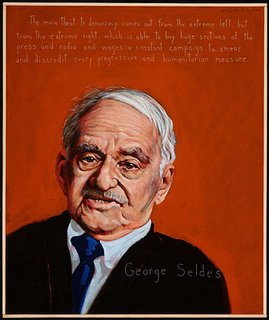Wartawan Berotak Kiri [4]
 ILLUSTRATED BY LAR
ILLUSTRATED BY LARMENJADI wartawan berarti menyembah fakta. Ketika menulis, pakailah imajinasi untuk mengungkapkannya. Simak contoh berikut:
Dan sepatu jang berat serta nakal
jang dulu biasa menempuh
djalan-djalan jang mengchawatirkan
dalam hidup lelaki yang kasar dan sengsara,
kini telah aku lepaskan
dan berganti dengan sandal rumah
jang tenteram, djinak dan sederhana
Sandal rumah itu memang telah dipakainja, tapi W.S. Rendra tidak mendjadi djinak. Uban dikepalanja makin bertambah, tapi begitu pula pandjang rambutnja. Kerut-kerut sudah mulai membajang disekitar matanja, tapi pandangan itu masih seperti tatapan anak kidjang – tjuma terkadang berkatjamata. Umur 36, anak 5, isteri 2: statistik ini bisa mengetjutkan laki-laki lain djadi runduk, tapi Rendra tidak runduk. Ia hampir tidak berubah.
Ia memang bukan lagi Willy jang menjeru ibunja “mamma” hingga disadjak-sadjak. Puisinja kini adalah gumpalan ekspresi yang lebih keras, bukan lagi baris-baris ballada dan njanjian manis. Hidup tak lagi ditemuinja seperti gadis ditemui djedjaka remadja, melainkan “hidup telah saja setubuhi dan keringat sudah membasahi randjang;” dan bagi Rendra, itulah sebabnja kemanisan tahun 1950-an susut dari sadjaknja, “karena saja agak kaget setelah mendjumpai hidup ini tidak lagi perawan.”[3]
Intinya, kalau ingin berbicara tentang buruh, berceritalah tentang pohon karet atau kelapa sawit. Kalau ingin meliput kehidupan sekelompok aktivis LSM, pilihlah tokoh yang bau keringatnya bisa tercium. Setidaknya, pelajarilah teknik Ayu Utami menggelitik bahasa lewat romannya, Saman.
Saya tidak menyarankan Anda menjadi sastrawan (meski apa salahnya jadi sastrawan?). Yang Anda butuhkan adalah kemauan untuk memastikan sel-sel otak kiri – tempat kemampuan berbahasa dikendalikan – tumbuh. Yang Anda lakukan adalah mengapresiasi semua karya sastra bermutu. Ini bagus untuk melatih kepekaan dalam berbahasa tulis dan kesehatan jiwa Anda sendiri. Dari situ, Anda akan mengenal kosa kata baru, gaya bertutur, pola-pola kalimat kompleks, paragraf-paragraf yang berkesan, bagaimana membangun ritme ketegangan dan kelucuan, menempatkan kutipan menarik, serta banyak lagi.
Tak berarti Anda harus mencangkok kata-kata sastrawi ke dalam karya jurnalistik. Dengan mengapresiasi karya sastra, Anda akan semakin yakin bahwa bahasa Indonesia punya fasilitas yang cukup bagi mereka yang mau memikat khalayaknya.
Terinspirasi oleh langgam sastra, para wartawan suka menciptakan penyosokan (profiling) terhadap sumber berita. Yang terkenal, misalnya, “manajer satu miliar” untuk menyebut Tanri Abeng. Atau, “kiai sejuta umat” untuk KH. Zainuddin Mz. Atau, “ratu goyang ngebor” untuk pesohor dangdut Ainur Rokhimah alias Inul Daratista. Atau, “seniman serba bisa” untuk Remy Silado. Atau, “paus sastra Indonesia” untuk H.B Jassin. Atau, “kaum sarungan” untuk nahdliyin.
Baru-baru ini, pers Inggris menjuluki Tony Blair sebagai “Tony teflon”, karena kata-kata si perdana menteri ternyata licin (seperti penggorengan teflon) alias bohong soal senjata pemusnah massal di Irak. Saya tidak tahu Paman Bush dijuluki apa.
Itu bagus, karena menunjukkan sang wartawan kreatif dan imajinatif. Pengelola pariwisata mesti berterima kasih kepada wartawan yang telah menyumbang kata “Pulau Dewata” bagi Bali.
Toh, Anda yang terobsesi pada kreativitas dalam penyosokan, tetaplah waspada. Penyosokan sumber berita juga harus mempertimbangkan relevansinya dengan konteks peristiwa. Umpama begini:
Preman asal Flores itu melakukan aksinya di Pasar Tanah Abang.
Penjudi ding-dong bermata sipit itu berusaha menyogok petugas.
Polisi menduga, pengusaha berkulit hitam itu sudah kabur ke luar negeri.
Penyosokan semacam itu bukan saja tidak relevan, tapi juga dapat melukai hati orang lain yang tak ada hubungannya dengan sumber berita. Seperti kata pepatah, untuk membuat kebakaran besar, kita cuma membutuhkan satu kali percikan api kecil. Ingatlah petatah-petitih: “Oleh pedang kita cuma mati sekali. Oleh kata kita terhina bergenerasi.”
Sejumlah wartawan kawakan seperti Mark Kramer, John Hersey, Jimmy Breslin, dan Truman Capote, bahkan mampu “menghidupkan” karya jurnalistik mereka melebihi gaya novelistik, menjadi sinematik. Simak nukilan reportase Hersey bertitel Hiroshima berikut:
I – A NOISELESS FLASH
At exactly fifteen minutes past eight in the morning, on August 6, 1945, Japanese time, at the moment when the atomic bomb flashed above Hiroshima, Miss Toshiko Sasaji, a clerk in the personnel department of the East Asian Tin Works, had just sat down at her place in the plant office and was turning her head to speak to the girl at the next desk. At the same moment, Dr. Masakazu Fujii was settling down cross-legged to read the Osaka Asahi on the porch of his private hospital, overhanging one of the seven deltaic rivers which divide Hiroshima; Mrs. Hatsuyo Nakamura, a tailor’s widow, stood by the window of her kitchen, watching a neighbor tearing down his house because it lay in the path of an air-raid-defense fire lane; Father Wilhelm Kleinsorge, a German priest of the Society of Jesus, reclined his underwear on a cot on the top floor of his order’s three-story mission house, reading a Jesuit magazine, Stimmen der Zeit: Dr. Terufumi Sasaki, a young member of surgical staff of the city’s large, modern Red Cross Hospital, walked along one of the hospital corridors with a blood specimen for a Wassermann test in his hand; and the Reverend Mr. Kiyoshi Tanimoto, pastor of the Hiroshima Methodist Church, paused at the door of a rich man’s house in Koi, the city’s western suburb. And prepared to unload a handcraft full of things he had evacuated from town in fear of the massive B-29 raid which everyone expected Hiroshima to suffer. A hundred thousand people were killed by the atomic bomb, and these six were among the survivors. They still wonder why they lived when so many others died. Each of them counts many small items of chance or volition – a step taken in time, a decision to go indoors, catching one streetcar instead of the next – that spared him. And now each knows that in the act of survival he lived a dozen lives and saw more death than he ever thought he would see. At the time, none of them knew anything.[4]
Atau, simaklah bagaimana Breslin menulis reportasenya tentang prosesi pemakaman jenazah John F. Kennedy. Kata-kata yang mengalir di situ seperti rekaman kamera video: bergerak.
Clifton Pollard was pretty sure he was going to be working on Sunday, so when he woke up at 9 a.m. in his three-room apartment on Corcoran Street, he put on khaki overalls before going into the kitchen for breakfast. His wife, Nettie, made bacon and eggs for him. Pollard was in the middle of eating them when he received the phone call he had been expecting.
It was from Mazo Kawalchik, who is the foreman of the gravediggers at Arlington National Cemetery, which is where Pollard works for a living. “Polly, could you please be here by eleven o’clock this morning?” Kawalchik asked. ”I guess you know what it’s for.”
Pollard did. He hung up the phone, finished breakfast, left his apartment so he could spend Sunday digging a grave for John Fitzgerald Kennedy.
When Pollard got to the row of yellow wooden garages where the cemetery equipment is stored, Kawalchik and John Metzler, the cemetery superintendent, were waiting for him.
“Sorry to pull you out like this on a Sunday,” Metzler said.
“Oh, don’t say that,” Pollard said. “Why, it’s an honor for me to be here.”
Pollard got behind the wheel of a machine called a reverse hoe. Gravedigging is not done with men and shovels at Arlington. The reverse hoe is a green machine with a yellow bucket which scoops the earth toward the operator, not away from it as a crane does. At the bottom of the hill in front of the the Tomb of the Unknown Soldier, Pollard started the digging.
Leaves covered the grass. When the yellow teeth of the reverse hoe first bit into the ground, the leaves made a threshing sound which could be heard above the motor of the machine. When the bucket came up with its first scoop of dirt, Metzler, the cemetery superintendent, walked over and looked at it.
“That’s nice soil,” Metzler said.
“I’d like to save a little of it,” Pollard said. “The machine made some tracks in the grass over here and I’d like to sort of fill them in and get some good grass growing there, I’d like to have everything, you know, nice.”
James Winners, another gravedigger, nodded. He said he would fill a couple of carts with this extra-good soil and take it back to the garage and grow good turf on it.
“He was a good man,” Pollard said.
“Yes, he was,” Metzler said.
“Now, they’re to come and put him right here in this grave I’m making up,” Pollard said. “You know, it’s an honor just for me to do this.”
Pollard is forty-two. He is a slim man with a mustache who was born in Pittsburgh and served as a private in the 352d Engineers battalion in Burma in World War II. He is an equipment operator, grade 10, which means he gets $3.01 an hour. One of the last to serve John Fitzgerald Kennedy, who was the thirty-fifth President of this country, was a working man who earns $3.01 an hour and said it was and honor to dig the grave.
Yesterday morning, at 11:15, Jacqueline Kennedy started walking toward the grave. She came out from under the north portico of the White House and slowly followed the body of her husband, which was in a flag-covered coffin that was strapped with two black leather belts to a black caisson that had polished brass axles. She walked straight and her head was high. She walked down the bluestone and blacktop driveway and through shadows thrown by the branches of seven leafless oak trees. She walked slowly past the sailors who held up flags of the states of this country. She walked past silent people who strained to see her and then, seeing her, dropped their heads and put their hands over their eyes. She walked out the northwest gate and into the middle of Pennsylvania Avenue. She walked with tight steps and her head was high and she followed the body of her murdered husband through the streets of Washington.
Everybody watched her while she walked. She is the mother of two fatherless children and she was walking into the history of this country because she was showing everybody who felt old and helpless and without hope that she had this terrible strength that everybody needed so badly. Even though they had killed her husband and his blood ran onto her lap while he died, she could walk through the streets and to his grave and help us all while she walked.
There was mass, and then the procession to Arlington. When she came up to the grave at the cemetery, the casket already was in place. It was set between brass railings and it was ready to be lowered into the ground. This must be the worst time of all, when a woman sees the coffin with her husband inside and it is in place to be burried under the earth. Now she knows that it is forever. Now there is nothing. There is no casket to kiss or hold with your hands. Nothing materials to cling to. But she walked up to the burial area and stood in front of a row of six green-covered chairs and she started to sit down, but then she got up quickly and stood straight because she was not going to sit down until the man directing the funeral told her what seat he wanted her to take.
The ceremonies began, with jet planes roaring overhead and leaves falling from the sky. On this hill behind the coffin, people prayed aloud. They were cameramen and writers and Secret Service men and they were saying prayers out loud and choking. In front of the grave, Lyndon Johnson kept his head turned to his right. He is President and he had to remain composed. It was better that he did not look at the casket and grave of John Fitzgerald Kennedy too often.
Then it was over and black limousines rushed under the cemetery trees and out onto the boulevard toward the White House.
“What time is it?” a man standing on the hill was asked. He looked at his watch.
“Twenty minutes past three,” he said.
Clifton Pollard wasn’t at the funeral. He was over behind the hill, digging graves for $3.01 an hour in another section of the cemetery. He didn’t know who the graves were for. He was just digging them and then covering them with boards.
“They’ll be used,” he said. “We just don’t know when.”
“I tried to go over to see the grave,” he said. “But it was so crowded a soldier told me I couldn’t get through. So I just stayed here and worked, sir. But I’ll get over there later a little bit. Just sort of look around and see how it is, you know. Like I told you, it’s an honor.”[5]
Bagaimana meliput optimisme pekerja kerah putih di tengah hiruk-pikuk metropolitan seperti Shanghai? Saya suka bagaimana Pamela Yatsko, seorang wartawati majalah Far Eastern Economic Review, menuliskan laporannya:
Jimmy Zou adalah seorang pegawai bank dan investasi milik provinsi di pelosok negeri. Kami bertemu sambil makan siang di Pasta Fresca, salah satu tempat makan baru masakan Italia di Shanghai. Mengenakan jas luar panjang dari bahan wol untuk melawan dinginnya musim dingin, pria berusia 30 tahun ini terlihat seperti orang kaya. Cincin emas bermata berlian menghiasi jarinya dan kantongnya menggembung berisi telepon seluler model baru – pada umumnya penduduk Shanghai waktu itu masih masih mengandalkan seranta.
“Apa maksud Anda bahwa Anda memunyai seorang teman di bursa saham yang membantu Anda memperoleh banyak uang?” tanya saya.
“Oh, dia (perempuan) menyampaikan berita baik kepada saya.”
“Apa maksud Anda dengan ‘berita baik’?”
“Dia memberitahu saya informasi di dalam cukup awal. Dia akan memberitahu saya saham-A yang sebaiknya dibeli, dan, tidak pernah meleset, dalam dua hari harganya akan naik.”
Memang berita baik. “Berapa banyak uang yang berhasil Anda peroleh tahun itu?”
“Oh, sekitar 200 ribu yuan,” katanya sambil tertawa kecil.
Zou memunyai uang banyak untuk bisa tertawa. Dua ratus ribu yuan bernilai sekitar 24.100 dolar AS. Dia cepat-cepat keluar dari biro turisme dan lebih memilih bisnis perdagangan saham untuk menjadi jutawan dalam arti yuan.
Pada waktu pelayan mengantarkan pesanan cappucino kami, Zou sudah merasa amat santai. “Kalau Anda mau, saya dapat melakukan sesuatu untuk Anda,” katanya, menatap lekat-lekat langsung ke mata saya.
“Tapi saya seorang asing. Saya tidak diperkenankan untuk berdagang saham-A,” jawab saya.
Tidak terkejut, Zou meneruskan: “Tahun 1997 akan menjadi tahun yang amat makmur. Saya amat yakin, bahwa semakin lama semakin banyak peluang yang menunggu kami. Di Cina, bila Anda ingin memperoleh uang, Anda hanya perlu membeli, membeli, membeli, dan pasar saham akan terus naik dan naik lagi! Anda hanya perlu mengetahui kapan menjual dan kapan membeli dan saya yakin mengenai kapan melakukannya. Saya yakin tahun ini saya dapat memperoleh laba 50 persen atau bahkan lebih besar lagi,” katanya sambil tersenyum lebar.
“Bagaimana mungkin Anda begitu pasti?”
“Pasar saham-A mula-mula akan menurun karena koreksi tetapi kemudian harganya akan naik karena ada modal menganggur dalam jumlah yang amat besar di Cina dan sedikit peluang investasi, jadi pasar saham merupakan satu-satunya pilihan … Anda tahu, orang-orang terkaya di Cina hanya mereka yang bermain dalam saham. Beberapa di antaranya tidak memunyai pendidikan tinggi. Tingkat budaya mereka rendah. Mereka tidak memahami seni. Tetapi mereka mengetahui cara mencari uang.”
Pelayan mengantarkan tagihan. Ketika saya membayar, saya bertanya kepada Zou apa pendapat keluarganya mengenai keberhasilannya. Sambil meremas hidung, dia menjawab, “Mereka ingin saya bekerja di sebuah kantor menjadi pejabat pemerintah atau insinyur. Mereka ingin saya menjadi pekerja kerah putih.”
“Tetapi Anda ADALAH pekerja kerah putih.”
“Mereka menduga saya penjudi. Tetapi sekarang, semakin lama semakin banyak orang Cina yang berjudi – dari profesor sampai pekerja sampai pengemis.”[6]
Bagaimana mencampurkan elemen deskripsi, narasi, percakapan, pengadeganan ke dalam loyang cerita yang utuh, silakan baca Harga Sebuah Keaslian.
Kutipan langsung dalam reportase bukanlah sekadar kiat untuk mendistribusi informasi. Ia juga unsur pemikat guna memuluskan jalan cerita. Ia merupakan sesuatu yang sangat penting, berharga, tidak bisa digantikan atau dihilangkan semau gue. Wartawan dan redaktur harus jeli memilih kutipan dari sumber berita untuk diletakkan pada konteks yang tepat.
Kutipan yang baik umumnya merupakan kiasan. Sifatnya orisinil, khas, dan eksklusif. Hingga hari ini, saya ingat kutipan-kutipan seperti:
“Lengser keprabon madek pandhita,” kata Presiden Soeharto.
“Tidak peduli kucing itu hitam atau putih, selama ia mampu menangkap tikus, ia adalah kucing yang baik,” kata Deng Xiao Ping.
“War can not be divorced from politics even for a single moment,” kata Mao Ze Dong.
“Read my lips,” kata Presiden Bill Clinton.
“History has called us,” kata Presiden George W. Bush.
“Gitu aja kok repot,” kata Gus Dur.
“Saya ini seperti mentimun. Bagaimana mungkin bisa melawan durian?” kata Amien Rais mengomentari kekalahannya dalam pemilu presiden.
“Quand la Chine sêvelera, le monde tremblera,” kata Raja Prancis, Napoleon Bonaparte, tahun 1817. Artinya, ketika Cina bangkit, dunia pun bergetar.
“Yang berani saya janjikan dalam sinetron ini adalah tanpa setan, tanpa kekerasan, dan tanpa pornografi,” kata Arswendo Atmowiloto, sutradara serial Keluarga Cemara.
“Ada tiga penemuan besar dalam peradaban, yaitu api, roda, dan Playboy,” canda Hugh Hefner, 77 tahun, pendiri majalah Playboy.
Memang, sedikit pejabat (terutama orde baru) di Indonesia yang punya pernyataan menarik untuk dikutip. Pernyataan mubazir lebih banyak. Mereka tak terlatih mengemukakan pemikiran atau gagasannya dengan cara sendiri, khas, dan orisinil. Di Amrik, George Seldes sampai membuat dua buku, The Great Quotations (1960) dan The Great Thoughts (1985), yang merupakan kumpulan gagasan dan kutipan terbaik dari sumber-sumber beritanya.
Jangan putus asa. Coba rangsang sumber berita Anda agar menjadi “dirinya sendiri” sewaktu wawancara. Sekali seumur hidup, saya pernah membaca kutipan terbaik dari Jendral (Purn.) TNI L.B Moerdani selama menjabat sebagai Menhankam. Ketika dimintai komentar tentang organisasi militer Israel, dia menjawab, “Saya suka tentara Israel. Di sana tidak ada perkumpulan seperti Dharma Wanita.”
Sebagai wartawan, sekurangnya Anda bertugas membantu orang-orang untuk mengerti apa yang terjadi di sekitar mereka; di desa, di kota, di negara, dan di dunia. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki kecakapan berbahasa seperti Anda. Anda harus bisa memilah peristiwa dan pokok isu yang paling rumit, lalu menyampaikannya ke dalam bahasa yang dapat dimengerti. Jika gagal melakukan hal ini, orang akan berhenti membeli suratkabar atau majalah Anda. Jika ini terjadi, saran saya: carilah pekerjaan lain.
[3] Dikutip dari Rendra, Dimanakah Kau Saudaraku oleh Goenawan Mohamad (Majalah Tempo, 1972).
[4] Dikutip dari Hiroshima oleh John Hersey (Majalah The New Yorker, 1946).
[5] Dikutip dari buku The Art of Fact (1984) yang disunting oleh Ben Yagoda.
[6] Dikutip dari New Shanghai oleh Pamela Yatsko (John Wiley & Sons, 2003).
9 Previous Page