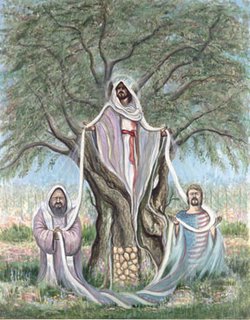Suami Berpengalaman
 ILLUSTRATED BY TAMARA DE LEMPICKA
ILLUSTRATED BY TAMARA DE LEMPICKASEBELAS tahun berbagi tempat tidur dengan satu perempuan yang sama, ternyata tidak lantas menjadikanku suami berpengalaman. Terima kasih apabila Anda bersimpati padaku, meskipun harus kukatakan bahwa bukan itu yang kumaksud. Kehidupan seks kami – jika itu yang Anda kira – masih berkobar-kobar, tetap panas, sepanas nyala api unggun. Setidaknya, sampai sejauh ini.
Harus kuakui, aku bukanlah jenis lelaki yang memesan tempat eksklusif untuk makan malam dalam keremangan cahaya lilin dengan pramusaji yang berjas dasi kupu-kupu. Selain tidak memenuhi harapannya, hampir pasti tidak memenuhi anggaranku. Aku juga bukan jenis lelaki yang memperlakukan pasangannya seperti porselen berharga, sehingga harus hati-hati merawatnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, aku bukan seseorang yang menjadi buntut istrinya – lebih praktis menunggu di toko buku – ketika shopping. Aku tak khawatir ketika, misalnya, ia pergi sendirian ke Pasar Tanah Abang. Sebab, aku merasa ia bisa melakukannya. Aku pernah membukakan pintu mobil untuknya, pernah menumis kangkung, pernah mengoperasikan mesin cuci, tapi apakah itu yang namanya suami berpengalaman? Sepertinya memang begitu.
Istri sebelas tahunku adalah seorang pembaca novel romansa tulen, yang rela melewatkan adegan seks untuk memperoleh “bagian yang menggetarkan.” Suatu bagian ketika si jagoan berjuang mendapatkan kembali kekasihnya, teguh mempertahankan prinsip yang diyakininya benar, yang membela cintanya sampai maut memisahkan mereka. Ia menyukai pengarang yang terbukti tak pernah gagal membuat pembacanya mengurai air mata, yang menghias adegan-adegan cinta dengan dialog cerdas, ucapan-ucapan yang tidak picisan seperti, “Andrea, kau tahu apa yang dokter temukan ketika membedahku? Ia menemukan namamu terukir di jantungku.” Atau, kalimat Mr. Fight yang berkata kepada Mrs. Right, “Duduklah, biar kubereskan.”
Semua pengarang itu telah mengajarkan poin penting kepada istriku: seorang lelaki tak harus menjadi arkeolog untuk menjadi suami berpengalaman, yang semakin mencintai istrinya sampai tua. Kedengarannya luar biasa, aku ingin sekali memercayai hal itu. Apa ada suami berpengalaman seperti itu dalam kehidupan nyata? Ada, bahkan mungkin banyak; pokoknya, terkecuali aku.
Pada suatu hari Minggu yang malas, kami memutuskan untuk mengunjungi teman lama, Aris dan Fitri. Mereka telah menikah selama 12 tahun, tanpa anak. Aris bekerja 9 to 5, Fitri berkarier penuh waktu sebagai housewife. Boleh dibilang, mereka sedikit dari pasangan yang sanggup menepis sinisme cinta sejati; bahwa cinta sejati itu seperti hantu, banyak yang membicarakannya tapi hanya sedikit yang pernah melihatnya. Atau, skeptisisme tentang perkawinan; bahwa perkawinan adalah perjamuan membosankan dengan hidangan pencuci mulut yang disajikan di awal acara. Aris yang tampan dan Fitri yang menarik, tidak seperti itu. Satu sama lain tidak sukar disenangkan; bisa sependiam pohon. Sopan santun; tahu kapan mereka harus berbicara. Kisah cinta mereka, konon, tidak punya masa kedaluwarsa.
Di mataku, Aris adalah lelaki yang menggunakan sebagian besar sisa hidupnya untuk menuju dan dari istrinya. Dari cara Aris memperlakukan istrinya, sudah membuatku mawas diri. Ketika ceret air mencuit-cuit di atas nyala kompor, belum sempat istrinya beranjak, Aris berkata, “Duduklah, biar aku yang lakukan.”
“Makasih, honey.” Dan, Fitri meneruskan obrolannya bersama kami. Mataku spontan beradu pandang dengan istriku yang mesam-mesem.
Ketika telepon berdering, terdengar suara Aris dari dapur, “Biar aku yang angkat, sayang!” Istriku sengaja memandangku sebentar. Alisnya terangkat, tersenyum penuh arti.
Beberapa saat kemudian, saat ketukan gembok di pintu pagar membuyarkan perhatian, Fitri mengintip dari balik gorden. Setelah meletakkan gagang telepon, Aris berseru, “Ya! Tunggu!”
Lalu, ia berkata lembut kepada istrinya, “Duduklah, biar aku yang lakukan.”
Kali ini, aku sudah siap memalingkan wajah dari pandangan yang sama dari orang yang sama.
Aris benar-benar sigap, sesigap tentara marinir dalam pendaratan pertama, berlari ke sana ke mari, benar-benar bisa diandalkan. Ia seakan tahu betul bagaimana seharusnya melayani dan melindungi. Sementara aku, si suami yang tak berpengalaman ini, begitu lamban, terutama saat tenggelam di sofa dekilnya bersama suratkabar.
Suami berpengalaman milik Fitri, itu pasti telah mengundang ratusan kupu-kupu berpesta pora di dalam pikiran istriku. Aris yang tampan saja bisa, kenapa kau tidak?; begitu mungkin benaknya. Ya, aku memang jauh dari tampan, tapi tak berarti tak punya perasaan. Aku justru jatuh kasihan pada Aris; sebaliknya, perasaanku terhadap sikap hangat Fitri berkurang.
Suami berpengalaman – dalam banyak cara – menyerupai komidi putar. Bisa menyenangkan, bisa pula memabukkan. Sementara ini aku tak berhasil memetik pelajaran dari mereka, karena menurutku, perempuan akan lebih menarik jika dapat membuat lelaki jatuh ke dalam pelukannya, bukan ke dalam genggaman tangannya.
Cimanggis, 16 Maret 2006