Fundamentalis versus Progresif
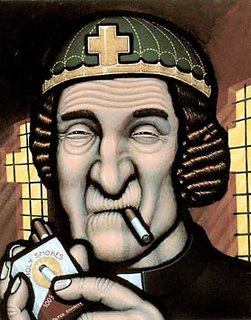 ILLUSTRATED BY TIM SLOWENSKI
ILLUSTRATED BY TIM SLOWENSKIKEKERASAN mewarnai perlawanan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan asing di daerah – itu kegagalan negara. Anarki mengancam pemilihan kepala daerah – itu kegagalan negara. Demonstrasi menyertai pro-kontra rancangan undang-undang – itu kegagalan negara. Kebrutalan umat beragama meruyak saat menghadapi penghayat “ajaran sesat” – itu kegagalan negara. Tak ada lagi ruang dialog bagi pertentangan pendapat – itu kegagalan negara. Betapa negara telah menjadi penjelasan yang begitu hebat bagi semua persoalan.
Saya berharap, Bung Piliang sedang bercanda ketika mencetuskan Demokrasi Fundamentalis (Kompas, 29 April 2006). Fundamentalis kelihatannya sekadar seloroh yang biasanya digunakan oleh kelompok liberal untuk menggambarkan kurangnya kedewasaan intelektual kelompok yang berpandangan konservatif. Ia juga tampak tidak serius ketika melontarkan pandangan sugestif, bahwa ada pertentangan antarfundamentalis dalam merespons persoalan mutakhir bangsa.
Pandangan tersebut tidak mengejutkan jika ditempatkan pada sebuah konteks amatan yang tepat. Sebuah perbandingan perlu menggabungkan pemahaman sejarah dan konteks peristiwa. Sukar dibayangkan jika dalam memahami fundamentalisme kita memisahkannya dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang merupakan salah satu pelecutnya. Namun, secara umum penyikapan terhadap sejumlah persoalan di Indonesia hari-hari ini – yang berakhir dengan huru-hara atau kekerasan – tidak lebih dari pertentangan antara kelompok fundamentalis dan kelompok progresif.
Klaim bahwa fundamentalisme penyebab terfragmentasinya masyarakat ke dalam kelompok sektarian, bisa diterima sebagai reaksi; bukan aksi yang sekonyong-konyong terlibat dalam konflik sekuler. Pembedaan ini penting, sekurangnya agar kita bisa memahami hakikat fundamentalisme dalam proporsi faktual. Sebab, kendati acapkali menggunakan aksi kekerasan, tidak semua fundamentalis berarti kekerasan sebagaimana tidak semua kekerasan bersifat fundamentalis. Bahkan seandainya kelompok sektarian terfragmentasi menjadi pelbagai pleton kecil masyarakat yang sama-sama fundamentalisnya, fundamentalisme bukanlah satu-satunya monster demokrasi yang menakutkan.
Pleton-pleton kecil tersebut umumnya bersifat dogmatis, doktriner, terlalu membesarkan-besarkan perbedaan kecil, dan beroperasi di luar batasan umum dalam sistem hukum. Sifat bawaan ini justru membuat mereka mudah terpecah-belah dan ditekuk negara.
Dengan corak yang ingin dikesankan sebagai watak fundamentalis, kelompok reaktif ini sebetulnya merupakan penyamaran (masquarade) dari premanisme. Pada kasus kerusuhan dalam pemilihan kepala daerah, gejalanya bahkan sudah terang-benderang. Tak terkecuali pada beberapa kasus, gejala penggunaan simbol atau atribut khusus juga bagian dari penyamaran untuk mencapai posisi tawar yang diharapkan. Singkatnya, refleksi kekerasan kaum fundamentalis sejati sebatas pretensi defensif (reaksi); bukan ofensif (aksi) dan partikular tanpa kejelasan artikulasi sebagaimana yang ditunjukkan oleh para preman.
Mereaksi Perubahan
Secara sosiologis, istilah “fundamentalis” ditujukan untuk menyebut gerakan-gerakan yang melancarkan reaksi terhadap persoalan akibat modernisasi. Di mata fundamentalis modernisasi adalah sumber segala kejahatan, seperti halnya kapitalisme dipandang dengan cara yang sama oleh kaum kiri revolusioner. Gerakan ini tumbuh dari komunitas lokal, berkembang secara persuasif dengan mengajak masyarakat luas agar taat pada tradisi nilai-nilai fundamental dan teks-teks otentik yang (dianggap) tanpa kesalahan. Tak segan-segan ia mencoba melirik kekuasaan politik – meraihnya jika diperlukan – demi mendesakkan kejayaan tradisi masa lampau.
Sebagaimana gerakan radikal lainnya, fundamentalis tidak berwajah monolitik terutama tentang watak kekerasan yang melekat dalam dirinya. Sebagian menganggap kekerasan sebagai suatu kewajaran – bahkan keharusan – sebagian lagi menentang keras. Perbedaan penyikapan terhadap kekerasan ini menentukan derajat toleransi mereka terhadap perbedaan atau the others.
Ukuran fundamentalisme sendiri dalam beberapa hal bersifat situasional. Penduduk Aceh dan Sumatra Barat mungkin sama-sama berhasrat untuk mengutamakan nilai-nilai tradisi keagamaan, melebihi ketaatan mereka terhadap norma-norma masyarakat. Penduduk Aceh tidak lebih fundamentalis ketimbang penduduk Sumatra Barat; penduduk Aceh hanya hidup dalam situasi yang lebih sulit.
Ketika menemukan “musuh bersama”, mungkin kita beranggapan bahwa kelompok fundamentalis akan bersatu. Memang demikian, seperti yang terjadi pada kelompok proRUU APP. Akan tetapi, kelompok kontra yang juga sama ngototnya tidak serta-merta merupakan fundamentalis. Atau, dalam tulisan Bung Piliang disebut “fundamentalisme keagamaan ultradogmatis” bertemu dengan “fundamentalisme kultural ultraliberalis.” Keduanya memang membela suatu prinsip yang menurut mereka fundamental, tapi tidak lantas kelompok kedua “harus” menjadi fundamentalis. Sebaliknya, kelompok kontra justru merepresentasikan relativisme, sesuatu yang amat dibutuhkan dalam demokrasi.
Relativisme praktis tidak mempertentangkan berbagai interpretasi atas kitab suci atau tradisi keagamaan, sehingga seharusnya ia mampu memuluskan interaksi sosial dan mengurangi munculnya pertentangan. Akan tetapi, relativisme justru merupakan ancaman bagi kaum fundamentalis yang mengklaim hanya ada satu kebenaran dan telah mereka dapatkan.
Oleh sebab itu, lebih tepat jika pertentangan mereka disebut “kelompok fundamentalis” bertemu dengan “kelompok progresif”. Kelompok pertama – ditandai oleh kelas sosial yang paling sedikit menikmati kesejahteraan ekonomi – menilai manusia berada dalam posisi sarat dosa dan berbahaya; mereka menuduh kelompok progresif sebagai iblis. Kelompok kedua, yang biasanya didukung oleh bukti kesuksesan manusia modern dalam mengendalikan dan memajukan lingkungannya, cenderung melihat kehidupan sebagai sesuatu yang baik dan membaik.
Peran Negara
Kegagalan negara umumnya disodorkan sebagai alasan ketika pertentangan antarkelompok masyarakat berujung kekerasan. Alasan tersebut cukup menentramkan, karena selain tak ada pihak yang bertentangan akan merasa dipersalahkan, negara bisa dipertukarkan dengan bersama.
Di masa lalu, saat demokrasi sosial gaya lama memandang keterlibatan pemerintah dalam kehidupan keluarga sebagai sesuatu yang terpuji, alasan tersebut masih relevan. Pada masa-masa di mana campur tangan negara terhadap pasar masih besar dan hak-hak politik warga terbelenggu, kegagalan negara pada banyak urusan merupakan tesis yang tak perlu diperdebatkan.
Globalisasi, betapa pun orang tak menyukainya, telah membuat demokrasi sosial gaya lama terpinggirkan. Ini tak berarti globalisasi menjadikan negara-bangsa sebuah “rekaan”, seperti klaim Kenichi Ohmae (The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies, 1995), sehingga pemerintah pun usang. Pada kenyataannya, globalisasi hanya “mempreteli” negara-bangsa dalam arti bahwa kekuasaan yang dulu terpusat pada negara, kini diperlemah oleh tuntutan desentralisasi dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat madani (civil society).
Badan-badan di luar pemerintah yang tak memiliki ciri transnasional tapi justru lokal, kini turut berperan dalam pemerintahan. Menurut Anthony Giddens dalam The Third Way: The Renewal of Social Democracy (1998), tak ada batas-batas permanen antara pemerintah dan masyarakat madani. Terkadang pemerintah masuk sampai jauh ke dalam arena masyarakat, kadangkala mundur dari arena itu, tergantung konteksnya. Situasi ini akan membuat negara akan kehilangan efektivitasnya jika ia bertahan pada pemusatan kekuasaan, apalagi bila dilakukan represif. Mau tak mau negara membatasi intervensinya.
Ketiadaan peran negara yang menyediakan “ruang dialog” bagi pertentangan antarkelompok masyarakat, hanya mengafirmasi tanda “negara tanpa musuh” (demokratis baru) versi Giddens, bahwa Indonesia di bawah pemerintahan sekarang memang menerapkan neoliberalisme. Mengikuti ortodoksi neoliberal – pasar-pasar global dibiarkan bebas menguasai, karena seperti pasar-pasar lainnya, mereka merupakan alat pemecah persoalan – pertentangan antarkelompok dewasa ini juga “dipaksa” menciptakan ekuilibrium.
Saya berharap, Bung Piliang sedang bercanda ketika mencetuskan Demokrasi Fundamentalis (Kompas, 29 April 2006). Fundamentalis kelihatannya sekadar seloroh yang biasanya digunakan oleh kelompok liberal untuk menggambarkan kurangnya kedewasaan intelektual kelompok yang berpandangan konservatif. Ia juga tampak tidak serius ketika melontarkan pandangan sugestif, bahwa ada pertentangan antarfundamentalis dalam merespons persoalan mutakhir bangsa.
Pandangan tersebut tidak mengejutkan jika ditempatkan pada sebuah konteks amatan yang tepat. Sebuah perbandingan perlu menggabungkan pemahaman sejarah dan konteks peristiwa. Sukar dibayangkan jika dalam memahami fundamentalisme kita memisahkannya dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang merupakan salah satu pelecutnya. Namun, secara umum penyikapan terhadap sejumlah persoalan di Indonesia hari-hari ini – yang berakhir dengan huru-hara atau kekerasan – tidak lebih dari pertentangan antara kelompok fundamentalis dan kelompok progresif.
Klaim bahwa fundamentalisme penyebab terfragmentasinya masyarakat ke dalam kelompok sektarian, bisa diterima sebagai reaksi; bukan aksi yang sekonyong-konyong terlibat dalam konflik sekuler. Pembedaan ini penting, sekurangnya agar kita bisa memahami hakikat fundamentalisme dalam proporsi faktual. Sebab, kendati acapkali menggunakan aksi kekerasan, tidak semua fundamentalis berarti kekerasan sebagaimana tidak semua kekerasan bersifat fundamentalis. Bahkan seandainya kelompok sektarian terfragmentasi menjadi pelbagai pleton kecil masyarakat yang sama-sama fundamentalisnya, fundamentalisme bukanlah satu-satunya monster demokrasi yang menakutkan.
Pleton-pleton kecil tersebut umumnya bersifat dogmatis, doktriner, terlalu membesarkan-besarkan perbedaan kecil, dan beroperasi di luar batasan umum dalam sistem hukum. Sifat bawaan ini justru membuat mereka mudah terpecah-belah dan ditekuk negara.
Dengan corak yang ingin dikesankan sebagai watak fundamentalis, kelompok reaktif ini sebetulnya merupakan penyamaran (masquarade) dari premanisme. Pada kasus kerusuhan dalam pemilihan kepala daerah, gejalanya bahkan sudah terang-benderang. Tak terkecuali pada beberapa kasus, gejala penggunaan simbol atau atribut khusus juga bagian dari penyamaran untuk mencapai posisi tawar yang diharapkan. Singkatnya, refleksi kekerasan kaum fundamentalis sejati sebatas pretensi defensif (reaksi); bukan ofensif (aksi) dan partikular tanpa kejelasan artikulasi sebagaimana yang ditunjukkan oleh para preman.
Mereaksi Perubahan
Secara sosiologis, istilah “fundamentalis” ditujukan untuk menyebut gerakan-gerakan yang melancarkan reaksi terhadap persoalan akibat modernisasi. Di mata fundamentalis modernisasi adalah sumber segala kejahatan, seperti halnya kapitalisme dipandang dengan cara yang sama oleh kaum kiri revolusioner. Gerakan ini tumbuh dari komunitas lokal, berkembang secara persuasif dengan mengajak masyarakat luas agar taat pada tradisi nilai-nilai fundamental dan teks-teks otentik yang (dianggap) tanpa kesalahan. Tak segan-segan ia mencoba melirik kekuasaan politik – meraihnya jika diperlukan – demi mendesakkan kejayaan tradisi masa lampau.
Sebagaimana gerakan radikal lainnya, fundamentalis tidak berwajah monolitik terutama tentang watak kekerasan yang melekat dalam dirinya. Sebagian menganggap kekerasan sebagai suatu kewajaran – bahkan keharusan – sebagian lagi menentang keras. Perbedaan penyikapan terhadap kekerasan ini menentukan derajat toleransi mereka terhadap perbedaan atau the others.
Ukuran fundamentalisme sendiri dalam beberapa hal bersifat situasional. Penduduk Aceh dan Sumatra Barat mungkin sama-sama berhasrat untuk mengutamakan nilai-nilai tradisi keagamaan, melebihi ketaatan mereka terhadap norma-norma masyarakat. Penduduk Aceh tidak lebih fundamentalis ketimbang penduduk Sumatra Barat; penduduk Aceh hanya hidup dalam situasi yang lebih sulit.
Ketika menemukan “musuh bersama”, mungkin kita beranggapan bahwa kelompok fundamentalis akan bersatu. Memang demikian, seperti yang terjadi pada kelompok proRUU APP. Akan tetapi, kelompok kontra yang juga sama ngototnya tidak serta-merta merupakan fundamentalis. Atau, dalam tulisan Bung Piliang disebut “fundamentalisme keagamaan ultradogmatis” bertemu dengan “fundamentalisme kultural ultraliberalis.” Keduanya memang membela suatu prinsip yang menurut mereka fundamental, tapi tidak lantas kelompok kedua “harus” menjadi fundamentalis. Sebaliknya, kelompok kontra justru merepresentasikan relativisme, sesuatu yang amat dibutuhkan dalam demokrasi.
Relativisme praktis tidak mempertentangkan berbagai interpretasi atas kitab suci atau tradisi keagamaan, sehingga seharusnya ia mampu memuluskan interaksi sosial dan mengurangi munculnya pertentangan. Akan tetapi, relativisme justru merupakan ancaman bagi kaum fundamentalis yang mengklaim hanya ada satu kebenaran dan telah mereka dapatkan.
Oleh sebab itu, lebih tepat jika pertentangan mereka disebut “kelompok fundamentalis” bertemu dengan “kelompok progresif”. Kelompok pertama – ditandai oleh kelas sosial yang paling sedikit menikmati kesejahteraan ekonomi – menilai manusia berada dalam posisi sarat dosa dan berbahaya; mereka menuduh kelompok progresif sebagai iblis. Kelompok kedua, yang biasanya didukung oleh bukti kesuksesan manusia modern dalam mengendalikan dan memajukan lingkungannya, cenderung melihat kehidupan sebagai sesuatu yang baik dan membaik.
Peran Negara
Kegagalan negara umumnya disodorkan sebagai alasan ketika pertentangan antarkelompok masyarakat berujung kekerasan. Alasan tersebut cukup menentramkan, karena selain tak ada pihak yang bertentangan akan merasa dipersalahkan, negara bisa dipertukarkan dengan bersama.
Di masa lalu, saat demokrasi sosial gaya lama memandang keterlibatan pemerintah dalam kehidupan keluarga sebagai sesuatu yang terpuji, alasan tersebut masih relevan. Pada masa-masa di mana campur tangan negara terhadap pasar masih besar dan hak-hak politik warga terbelenggu, kegagalan negara pada banyak urusan merupakan tesis yang tak perlu diperdebatkan.
Globalisasi, betapa pun orang tak menyukainya, telah membuat demokrasi sosial gaya lama terpinggirkan. Ini tak berarti globalisasi menjadikan negara-bangsa sebuah “rekaan”, seperti klaim Kenichi Ohmae (The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies, 1995), sehingga pemerintah pun usang. Pada kenyataannya, globalisasi hanya “mempreteli” negara-bangsa dalam arti bahwa kekuasaan yang dulu terpusat pada negara, kini diperlemah oleh tuntutan desentralisasi dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat madani (civil society).
Badan-badan di luar pemerintah yang tak memiliki ciri transnasional tapi justru lokal, kini turut berperan dalam pemerintahan. Menurut Anthony Giddens dalam The Third Way: The Renewal of Social Democracy (1998), tak ada batas-batas permanen antara pemerintah dan masyarakat madani. Terkadang pemerintah masuk sampai jauh ke dalam arena masyarakat, kadangkala mundur dari arena itu, tergantung konteksnya. Situasi ini akan membuat negara akan kehilangan efektivitasnya jika ia bertahan pada pemusatan kekuasaan, apalagi bila dilakukan represif. Mau tak mau negara membatasi intervensinya.
Ketiadaan peran negara yang menyediakan “ruang dialog” bagi pertentangan antarkelompok masyarakat, hanya mengafirmasi tanda “negara tanpa musuh” (demokratis baru) versi Giddens, bahwa Indonesia di bawah pemerintahan sekarang memang menerapkan neoliberalisme. Mengikuti ortodoksi neoliberal – pasar-pasar global dibiarkan bebas menguasai, karena seperti pasar-pasar lainnya, mereka merupakan alat pemecah persoalan – pertentangan antarkelompok dewasa ini juga “dipaksa” menciptakan ekuilibrium.
Cimanggis, 30 April 2006



